Oleh : Dimas Harits, S.T.,M.T
Kelapa sawit, sejenis tumbuhan bergenus Elaeis dari ordo Arecaceae, bertangkai tunggal dan dapat tumbuh hingga 20 meter tingginya. Buahnya berwarna merah cerah berbiji tunggal. Antara biji dan kulitnya terdapat lapisan minyak. Tidak hanya itu, biji putihnya pun bagaikan inti bumi, menggiurkan, sumber minyak nabati terbesar dunia. Tanaman ini divanya Indonesia, begitu kata orang.
Uniknya, tanaman ini bukan flora asli Indonesia. Sepertinya kita harus ‘berterimakasih’ atas jasa Hindia Belanda menjaga, merawat dan membawa tanaman ini dari Afrika Barat nun jauh disana ke tanah air kita tercinta tahun 1848. Pasalnya, tanaman ini tumbuh subur meluas dan dibudidayakan di Sumatra dan Kalimantan, namun mendekati musnah dinegara asalnya.
Sawit hanya dapat tumbuh subur dan produktif didaerah tropis sepanjang daerah khatulistiwa dengan curah hujan melimpah. Negara-negara khatulistiwa seperti Indonesia, Malaysia, sebagian Afrika Barat dan sebagian kecil lagi Amerika Latin merupakan negara-negara yang tepat dalam pembudidayaan sawit. Sayangnya, entah karena peristiwa politik atau faktor lingkungan, kebun-kebun sawit yang eksis hingga saat ini hanya ada di Indonesia dan Malaysia. Sebagianya merupakan kebun peniggalan masa penjajahan Inggris dan Belanda.
Indonesia merupakan produsen terbesar Crude Palm Oil (CPO) dunia dengan total kontribusi sebesar 60% terhadap produksi global. Dengan total kontribusi sebesar itu, dapat dibayangkan berapa luasan hektar bumi Indonesia, bumi Kalimantan dan Sumatra yang ditutupi pasak-pasak raksasa sawit.
Ibarat buah simalakama, dibalik isu dan dampak kerusakan lingkungan perkebunan sawit, manfaat sawit bagi masyarakat dan negara ternyata cukup menggiurkan. Dalam catatan Wibowo et al (2019) terdapat total seluas 14,03 juta ha lahan perkebunan sawit di Indonesia dengan 5.418.413 ha berasal dari kawasan hutan alih fungsi melalui mekanisme pelepasan. Dengan kata lain, sekitar 36% perkebunan sawit di Indonesia berasal dari kawasan hutan.
Dilain sisi, dengan luasan tersebut, total produksi nasional bisa mencapai 48,68 juta ton pertahun, melibatkan sejumlah 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung pada perkebunan berskala perusahaan serta 4,6 juta pekerja pada perkebunan tradisional yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat (Tempo, 2018).
Sebagai negara produsen terbesar, Indonesia sedikit bertaji dimata Internasional terkait tata kelola produk-produk CPO dan olahanya. Beberapa program-program yang diambil oleh pemerintah Jokowi terbilang cukup berani, semisal rencana penerapan program B40 menyusul adiknya, program B30, ditengah-tengah ancaman krisis energi fosil akibat perang Rusia Ukraiana. Program prioritas ini menempatkan Indonesia sebagai negara produsen Biofuel terbesar dunia.
Program B30, atau secara singkat dijelaskan sebagai program produksi bahan bakar dengan komposisi 30% Nabati (minyak sawit) dan 70% minyak fosil telah berjalan baik pertahun 2020. Total alokasi biodiesel pada tahun 2021 kemarin sebesar 9,2 juta kL dan terealisasi sebesar 4,3 juta kL untuk pasar dalam negeri. Pada semester pertama, Indonesia memperoleh keuntungan sebesar Rp 29,9 Triliun yang terdiri dari penghematan devisa sebesar Rp 24,6 Triliun dan nilai tambah CPO menjadi Biodiesel sebesar Rp 5,3 Triliun serta pengurangan emisi Co2 sebesar 11,4 juta ton Co2e (Zainal Abdi, 2021).
Melihat hasil ini, Eropa sedikit ketar ketir. Setalah niatan ini tercium, tahun 2018 melalui Kebijakan RED II (Renewble Energy Directive II) Uni-Eropa mengkategorikan minyak sawit sebagai komoditas beresiko tinggi terhadap deforestasi. Dampaknya, per tahun 2024 nanti, ketergantungan Eropa terhadap minyak sawit sebagai bahan baku olahan termasuk campuran biofuel harus dikurangi secara bertahap. Dengan kata lain, Indonesia terancam kehilangan pasar potensial mereka pertahun 2024.
Walaupun demikian kebutuhan dunia terhadap komoditas CPO, baik dalam bentuk olahan maupun mentahan tetap menunjukan angka yang cukup tinggi. Eropa tetap menjadi konsumen utama, disusul India dan Tiongkok (Zainal Abdi, 2021). Hal ini menunjukan, dibalik manuver politik perdagangan Uni-Eropa yang cenderung diskriminatif, mereka belum memperoleh sumber pengganti potensial bagi CPO yang berharga murah dan multiguna.
Kebijakan B30 pemerintah Indonesia tidak hanya membawa dampak positif, namun juga dampak negatif yang hingga saat ini kita rasakan. Berdasarkan data Gabungan Pengusahan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) program ambisius ini menggunakan 24% dari total produksi CPO Indonesia pada tahun 2020. Hal ini juga diiringi turunya pangsa CPO yang digunakan untuk produksi komoditas pangan termasuk minyak goreng (GAPKI, 2022).
Dewi Fortuna kurang berpihak pada Indonesia. Baru berjalan 1,5 tahun program ini harus menghadapi tantangan berat. Harga jual CPO dunia meningkat. Beberapa spekulasi bermunculan, mulai dari upaya negara-negara lain menghentikan program ambisius tersebut hingga pengaruh pandemi Covid-19 di negara-negara produsen sawit terbesar, Malaysia dan Indonesia.
Sepanjang tahun 2021, harga CPO di pasar Internasional naik signifikan sebesar 36,3% dibanding harga pada tahun 2020 (Majalah Sawit Indonesia, 2022). Data produksi CPO pada tahun 2021 menunjukan penurunan sebesar 0,9% dari tahun 2019. Selain mengalami tren penurunan, permintaan CPO dunia juga semakin meningkat, mengingat proses pemulihan pasca pandemi mulai menghidupkan perekonomian negara importir utama CPO.
Pemerintah ibarat menelan buah simalakama. Satu sisi program ambisius ini terlanjut memperlihatkan dampak dan potensinya. Sisi lain, pemerintah harus berbenah mempersiapkan berbagai program-program jangka pendek dan strategi-strategi jangka panjang penanggulangan kenaikan harga jual CPO.
Pertanyaan selanjutnya adalah, jika harga jual CPO naik, bukanya itu menguntungkan bagi Indonesia? Perlu kita ketahui bersama, harga jual CPO ditanah air mengikuti patokan harga lelang yang berkorelasi langsung denga harga internasional. Karena besarnya permintaan dari luar yang lebih menguntungkan, ketersediaan CPO untuk bahan olahan makanan dalam negeri semakin terancam.
Pemerintah mengantisipasi langkah ini dengan pemberian subsidi minyak goreng, penerapan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng pada pertengahan 2021 lalu. Melalui program DMO dan DPO, pemerintah memaksa eskportir CPO untuk menjual 20% hasil produksinya dengan harga sebesar Rp 9300/kg dibawah harga internasional sebesar Rp 15.000/kg untuk kebutuhan olahan domestik dalam negeri.
Langkah ini merupakan langkah yang sangat tepat. Seperti dilansir katadata.co.id, melalui program DMO, pemerintah berhasil mengamankan 415 ribu ton CPO yang diperuntukan bagi produksi olahan dalam negeri sejak pertengah Februari lalu. Bahkan jumlah ini melebihi jumlah ketersediaan bahan baku dimasa-masa normal yang hanya memerlukan 330 ribu ton.
Dilansir pada laman yang sama, data kementrian perdagangan menunjukan total penyaluran minyak goreng ke distributor sudah mencapai angka 519,73 juta liter. Dengan kata lain, jika Indonesia berpenduduk 270 juta orang, dalam sebulan satu orangnya hingga ke bayi-bayi baru lahir mendapat jatah masing-masing 2 liter. Sayangnya pemerintah masih sulit menurunkan harga minyak goreng dibawah harga tertinggi yang ditetapkan. Tidak hanya itu, apa yang ditakutkan oleh pemerintah juga terjadi, kelangkaan minyak goreng terjadi dimana-mana.
Antrian minyak goreng menjadi latar sosial media, memantik panic buying masyarakat. Bukanya solidaritas untuk saling berbagi, beberapa oknum justru memanfaatkan kepanikan ini untuk menimbun minyak goreng, membocorkan jalur distribusinya, kemudian mendapat keuntungan berkali-kali lipat melalui ekspor minyak goreng bersubsidi dengan harga pasar internasional ke luar negeri. Instansi-instansi, lembaga atau partai-partai politik yang membeli minyak goreng dari produsen untuk dibagi dan dijual dengan harga murah dalam rangka mengurangi beban masyarakat malah dituduh penimbun, pansos oleh nitizen. Nurani ditengah krisis seperti ini benar-benar diadu.
Pemerintah terpojok dan serba salah. Ibarat menjaga dua buah gawang, pemerintah tertatih-tatih menjaga keberlangsungan program ambisium B30 serta menjaga kestabilan harga dan kelangkaan minyak goreng di tanah air.
Masyarakat menjerit, petani sawit tradsional meringis. Pengalihan subsidi minyak goreng kemasan keminyak goreng curah per 16 maret kemarin ibarat menyiram minyak dalam api. Keberadaan minyak goreng curah terbukti sangat urgen ditengah kelangkaan minyak goreng kemasan. Pengalihan subsidi keminyak goreng curah justru membuka gerbang penimbunan dan kelangkaan minyak goreng curah ditengah-tengah pasar.
Pemerintah harus berbenah. Pembangungan infrakstruktur produksi serta penunjangnya harus dibarengi dengan pembangunan SDM dan lingkungan bisnis yang berintegritas (unggul), mandiri dan penuh kepedulian (berbudaya). Tanpa itu semua, campur tangan pemerintah pada pasar ibarat tambal sulam, menutup satu masalah untuk membuka dua, tiga, empat masalah baru.
Indonesia terus bertumbuh. Masuknya Indonesia pada barisan negara-negara G20 merupakan pengakuan resmi dunia terhadap lejitan perekonomian Indonesia. Pemanfaatan CPO sebagai campuran bahan bakar ramah lingkungan ibarat emas berharga dunia. Tata kelolanya benar-benar harus menjadi perhatian pemerintah.
Di sisi lain, dunia global terus memandang tata kelola perkebunan sawit Indonesia dengan padangan sinis. Isu perusakan lingkungan, minimnya upah buruh dan lain-lain mendorong kampanye-kampanye negatif barat terhadap pemanfaatan CPO yang lebih luas. Sekitar 2020 lalu beberapa produsen makanan dan bahan-bahan habis pakai mengalakkan kampanya “palm oil free” pada produk-produk mereka.
Pemerintah harus menjawab tantangan ini. Kebijakan sustainable development goals (SDGs) dengan standar budidaya sawit berkelanjutan melalui rountable sustainable palm oil (RSPO) dan Indonesia sustainable palm oil (ISPO) harus dipantau, ditata dan dirawat keterlaksanaanya.
Ketergantungan pada tata kelola ekstentif melalui mekanisme perluasan lahan sawit perlu dialihkan menjadi program tata kelola intentif melalui peremajaan lahan, pemberdayaan petani-petani tradisional, ketersediaan pupuk berkualitas dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
Nasib petani-petani tradisional yang cenderung termarjinalkan kiranya diperhatikan. Program -program intentifikasi produktifitas sawit jarang menyasar petani-petani tradisional akibat status pemanfaatan lahan yang belum jelas. Paket resolusi agraria kiranya dapat diterapkan dalam rangka mendorong formalisasi tenure lahan sawit petani tradisional yang bermasalah. Melalui dukungan preforma PPTKH dan perhutanan sosial, modal awal menuju formaliasi tersebut nyata didepan mata. Sistem tenur yang legal dan formal mendukung industrialisasi lahan sawit yang dikelola masyarakat secara tradisional, sehingga kesejahteraan petani tradisional semakin baik, ketersediaan dan produktifitas sawit dan olahanya pun akan semakin meningkat. (*)






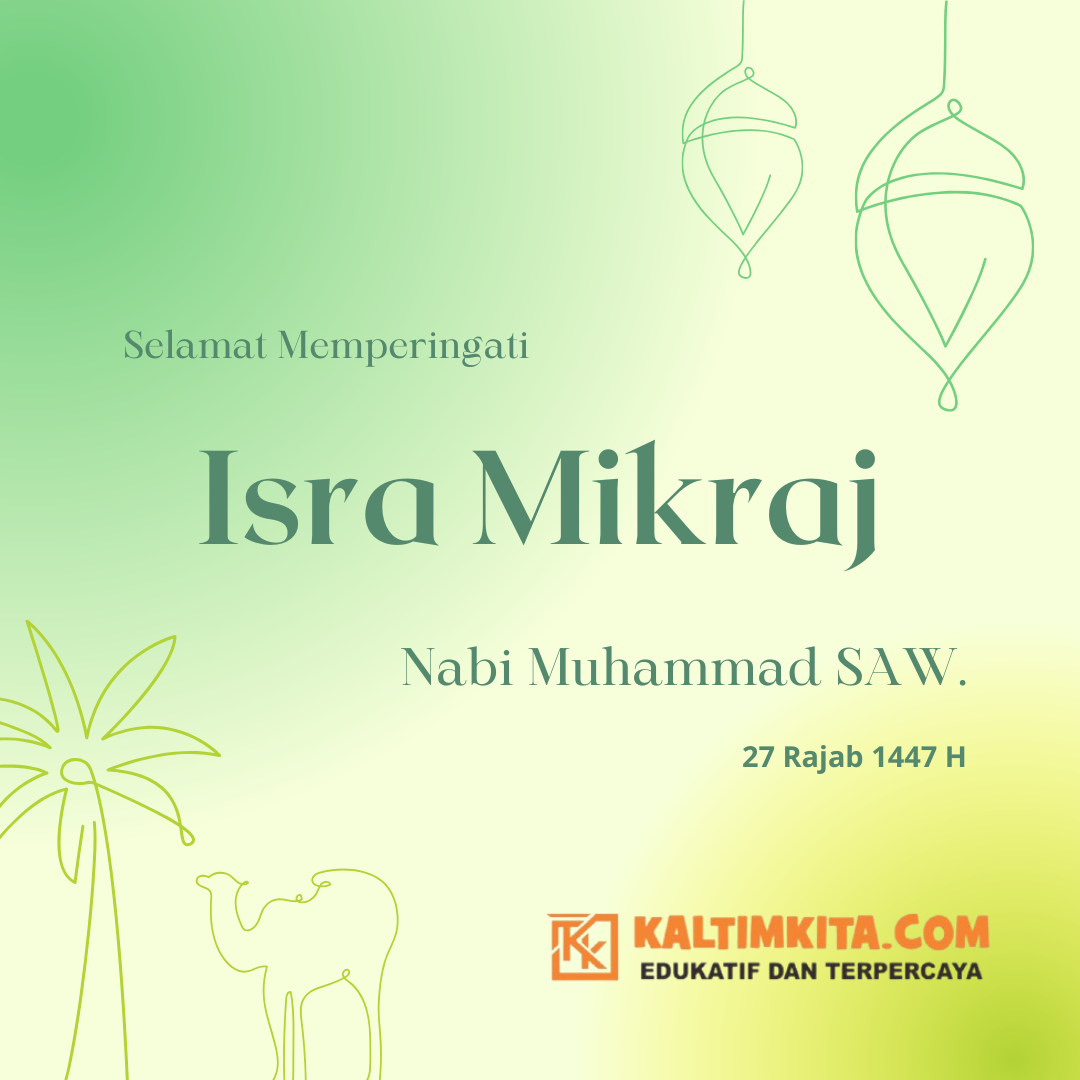








.jpg)
.jpg)









.jpg)




